Metalgear Music – Industri kreatif kadang merasa dirinya paling progresif. Paling bebas. Paling sadar isu. Tapi berkali-kali, justru dari ruang yang mengklaim diri “aman” dan “kolektif” inilah cerita-cerita pelecehan muncul ke permukaan.
Dugaan kasus yang menyeret nama owner brand lokal kembali membongkar fakta pahit kamera, studio, dan proses kreatif yang seharusnya profesional, kerap berubah jadi ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan. Tidak jarang bukan cuma di fashion, tapi juga di musik, visual art, hingga skena independen yang sering bersembunyi di balik kata “kebersamaan”.
Kita tidak fokus membicarakan kasus brand lokal, melainkan langkah lain dalam mencegah tindakan pelecehan seksual.
Pemotretan sejak lama bukan sekadar urusan teknis. Di dalamnya ada relasi kuasa yang jarang dibicarakan secara jujur. Owner brand, art director, fotografer, dan tim kreatif memegang kontrol penuh atas konsep, waktu, hingga ruang, sementara model sering kali menjadi tenaga freelance tanpa kontrak kuat, dan bisa berada di posisi paling rentan. Banyak dugaan pelecehan tidak terjadi di tengah keramaian, melainkan justru setelah kamera dimatikan, ketika semua orang pulang dan hanya tersisa dua pihak dengan dalih profesionalisme. Kalimat seperti “lanjutin bentar buat konsep” atau “cuma ngobrol evaluasi” terdengar biasa, tapi dalam praktiknya bisa menjadi pintu masuk penyalahgunaan.
Baca Juga: Beberapa Musisi yang Terang-terangan Anti-Zionisme dan Trump, Gak Main Aman!

Proses Digital Tidak Dilakukan oleh Wujud Berhasrat
Di tengah kegagalan proses ini, teknologi yang selama ini dicurigai justru menawarkan fungsi yang tak terduga. AI-generated model photography hadir bukan hanya sebagai alat produksi instan, tapi juga sebagai semacam “firewall”. Dengan model virtual, tidak ada tubuh manusia yang perlu hadir di studio, tidak ada interaksi fisik, dan tidak ada relasi kuasa yang bisa dimanipulasi. Semua berhenti di layar. Dalam konteks pencegahan, AI memang dingin, tapi justru di situlah nilainya. Ia memotong potensi pelecehan dari akar, bukan menunggu kejadian lalu sibuk meminta maaf.
Di industri musik, fungsi ini terasa semakin relevan. Visual band, artwork album, poster tur, hingga konten merch kini tidak lagi selalu membutuhkan sesi pemotretan konvensional. AI memungkinkan band atau brand menciptakan citra visual tanpa harus menciptakan ruang yang rawan. Bukan berarti AI lebih bermoral, tapi karena ia tidak punya hasrat. Nafsu bukan datang dari teknologi, melainkan dari manusia yang diberi kuasa tanpa kontrol.
Namun, menganggap AI sebagai solusi tunggal juga berbahaya. Di balik efisiensi dan rasa aman yang ditawarkan, ada harga besar yang harus dibayar. Ketika AI menjadi jalan pintas, pekerjaan model, fotografer, stylist, make-up artist, dan kru kreatif perlahan terkikis. Visual menjadi cepat, murah, dan steril, tapi kehilangan sentuhan manusia yang selama ini menjadi jantung ekspresi kreatif. Tidak ada lagi momen spontan di lokasi shoot, tidak ada chaos yang justru sering melahirkan estetika ikonik, tidak ada cerita keringat, lelah, dan interaksi yang membangun karakter visual.
Baca Juga: Bikin Event Musik, Udah Mikirin Biaya Masa Harus Bayar Pungli? Mau Sampai Kapan?
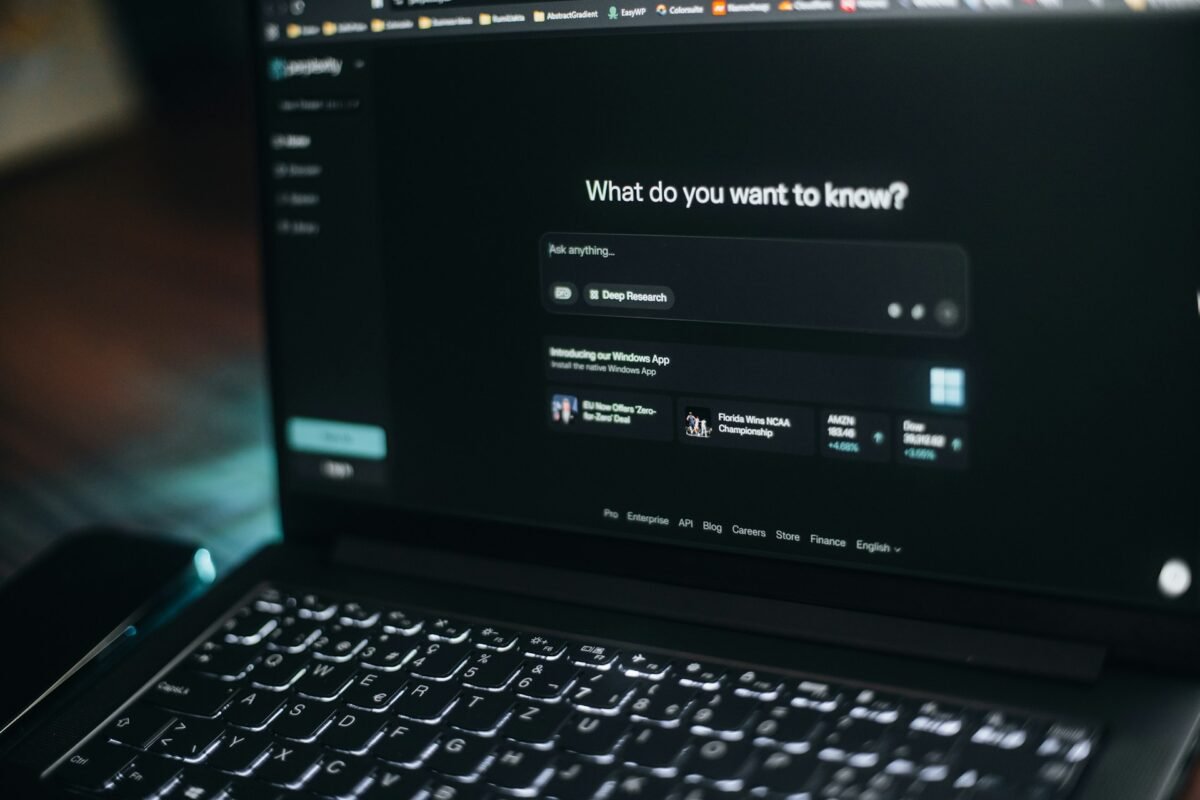
Digital Juga Punya Kekurangannya
Bagi skena musik, terutama yang bergerak di wilayah ekstrem dan underground, ini menjadi dilema serius. Musik keras lahir dari pengalaman manusia yang nyata amarah, luka, kekacauan dan visualnya sering kali membawa energi yang sama. AI bisa menciptakan wajah sempurna dan komposisi presisi, tapi ia tidak punya sejarah, tidak membawa beban emosional yang membuat sebuah visual terasa hidup. Ketika AI diandalkan secara berlebihan, yang hilang bukan cuma lapangan kerja, tapi juga jiwa kolektif yang selama ini membentuk identitas skena.
Karena itu, perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada pilihan hitam-putih antara AI atau manusia. Masalah utamanya bukan teknologi, melainkan kegagalan industri kreatif membangun sistem yang aman. AI bisa menjadi alternatif, alat bantu, atau solusi sementara ketika keselamatan tidak bisa dijamin. Di saat yang sama, penggunaan manusia dalam proses kreatif harus dibarengi dengan kontrak yang jelas, SOP ketat, dan mekanisme perlindungan yang nyata, bukan sekadar jargon.
Kasus dugaan pelecehan yang mencuat belakangan seharusnya menjadi momen evaluasi kolektif, bukan sekadar drama timeline atau bahan cancel culture. Ini adalah pengingat bahwa kreativitas tanpa etika hanyalah eksploitasi yang dibungkus estetika.

Sebagai Langkah Pencegahan
Jika industri kreatif masih gagal melindungi manusianya sendiri, maka tidak aneh jika teknologi mulai mengambil peran sebagai penyangga. Bukan untuk menggantikan seni, tetapi untuk menutup celah kekerasan yang selama ini dibiarkan menganga.
AI memang dingin dan tak punya empati, tapi justru karena itu ia tidak punya niat. Di sisi lain, manusia yang menciptakan dan menggunakan seni punya tanggung jawab moral yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Yang menentukan apakah ruang kreatif menjadi aman atau beracun tetap manusia di dalamnya. Dan selama itu belum dibenahi, AI akan terus dianggap bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tameng terakhir dari kegagalan etika industri kreatif itu sendiri.
Baca Juga: Sementara Ini, Apakah Kita Sedang Mengecilkan Tombol Volumenya?










